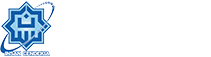Mewaspadai Nilai Kebebasan dalam Bacaan Sastra Siber Remaja
Oleh : Atik Khikmiyati, S.S.,S.Pd., M.Pd.
Saya memulai tulisan ini bersamaan dengan berakhirnya bacaan saya pada novel
Tentang Kamu karya Tere Liye yang menemani perjalanan dinas luar
daerah saya dari Malang Surabaya hingga Gorontalo. Novel tersebut
sebenarnya titipan dari Ibu saya untuk adik yang sedang belajar di Gorontalo.
Saya hanya butuh waktu sehari di atas pesawat dan transit satu kali
bandara untuk menghabiskan halamannya. Cerita awal pembuka tulisan ini terasa
tidak nyambung dengan judul tulisan di atas karena sejatinya saya bukan
penikmat sastra siber. Sebagaimana generasi yang lahir di tahun 80-an
lainnya, saya adalah generasi literasi kertas yang belajar mengeja kata dan
menulis kalimat dari buku paket di sekolah dengan tokoh utama si Budi di
dalamnya. Di masa remaja profil tokoh literasi saya juga Rangga, siswa SMA yang
pandai menulis puisi dan selalu membawa buku Aku, karya Sjuman
Djaya dalam film Ada Apa dengan Cinta? . Ide menulis tentang
sastra siber sebenarnya datang dari curhatan salah satu wali murid saya jauh
hari sebelumnya.
Garis
besar curhatan wali murid tersebut adalah tentang kekhawatiran dan
keterkejutannya pada sikap putrinya yang mengalami masalah belajar karena telah
kecanduan membaca novel online. Candu? Jika kata candu yang muncul
berarti ada dampak negatif, seperti kecanduan rokok, kecanduan narkoba,
kecanduan alkohol dan lain sebagainya. Betulkah novel atau sastra bisa menjadi
candu? Sangat mungkin, karena sastra bukan hanya bentuk ekspresi individu
sastrawan, sebaliknya sastra dari sejak awal penciptaannya sangat mungkin
dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan nilai-nilai tertentu. Pada situasi
tertentu, penyampaian nilai melalui media sastra jauh lebih mengena,
bahkan tentu saja berbahaya (jika nilai yang dibawa adalah nilai yang
bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut individu atau masyarakat tertentu)
dibandingkan media lainnya.
Mari kita
kembali ke curhatan wali murid saya. Salah seorang teman yang juga mendengar
curhatan tersebut penasaran dan mulai mencoba mengunjungi beberapa situs
penyedia novel online. Keesokan harinya, teman saya yang punya
bayi usia delapan bulan tersebut pun ngomel-ngomel karena sadar seluruh
pekerjaannya hari itu menjadi terbengkalai demi memenuhi rasa penasarannya
ingin menyelesaikan novel onlinenya. Hahahaha. Kondisi ini tentu saja
mematik niat di hati saya untuk secara lebih dalam menelusuri topik ini. Saya
tekankan di sini menelusuri, bukan membaca novel online. Jujur, saya
juga menjadi khawatir.
Eka
Kurniawan (2019) dan banyak krtikus satra lainnya menyebut fenomena sastra
siber sebagai gerakan perlawanan terhadap dominasi sastra koran. Ditinjau dari
kajian media, redaktur senior Tempo tersebut menyebut sastra siber
sebagai feuilleton baru sebagaimana peran munculnya ruang sastra di
media koran sebelumnya. Feuilleton adalah bagian atau ruang dari surat
kabar Eropa yang dinisbahkan untuk materi yang dirancang menghibur pembaca.
Jadi, di awal kemunculannya sastra koran sebenarnya hanya suplemen ringan bagi
kolom utama di koran umum. Namun, dalam perkembangannnya suplemen ruang sastra
ini menjadi mendominasi sehingga muncul anggapan bahwa “Anda belum menjadi
penuls hebat sebelum karya Anda dimuat di koran”. Prestise adalah alasan utama
mengapa anggapan ini muncul, karena sebanyak dan sebagus apa pun munculnya
karya sastra di koran umum tidak bisa mengubah status koran tersebut menjadi
koran atau media khusus sastra. Nah, sastra siber yang sebenarnya di awal
kemunculannnya dalam bahasa Eka Kurniawan adalah aktivitas iseng para penulis
ingin mendobrak dominasi tersebut.
Lalu seberapa jauh pengaruh sastra siber bagi pembacanya? Terutama pembaca
remaja, lebih khusus lagi siswa. Di titik inilah cerita pengalaman saya membaca
Tentang Kamunya Tere Liye menjadi terkait. Sebenarnya tidak ada
perbedaan mendasar dari segi struktur karya antara karya sastra siber dan
sastra kertas atau konvensional. Sebagaimana Eka Kurniawan menyampaikan sastra
siber sejatinya tidak menghandirkan aliran sastra baru bagi dunia sastra kita.
Ketertarikan saya pada cerita kisah hidup Sri Ningsih dan kemampuan Tere Liye
mengatur alur lah yang membuat saya betah membaca terus novel tersebut
sepanjang perjalanan hingga aktivitas menanti jadwal pesawat di bandara atau
duduk di dalam pesawat berjam-jam menjadi tak terasa. Hal serupa tentu
juga dialami siswa saya yang oleh orang tuanya disebut sedang mengalami
kecanduan. Lalu, apa yang membedakan sehingga muncul kesan mengganggu atau
kecanduan? Jawabannya adalah pada media yang digunakan.
Karakter utama karya sastra siber adalah digitalitas dan komunikasi
digitalnya dengan pembaca. Sebagaimana komunikasi di dunia maya lainnya seperti
facebook, instagram, whatsup aktivitas membaca
sastra melalui media digital lebih banyak menguras waktu dan melenakan pembaca.
Di masa lalu cerita sampainya sebuah karya misalnya novel ke tangan pembaca
lebih panjang dan sedikit romantis (aspek ini yang sekarang hilang) seperti
cerita saya di atas. Pembaca harus pergi ke toko buku di hari Minggu bersama
keluarga, ke perpustakaan, pinjam teman atau bahkan menabung dulu jika ingin
membaca buku impiannya. Di masa sekarang, sebagaimana facebook, instagram,
dan platform sosial lainnya penyedia bacaan sastra online telah
menjamur dan menyediakan begitu banyak pilihan bacaan bagi siapa saja di tangan
mereka. Cukup bermodalkan data atau jaringan internet dan sekali sentuh
pembaca bisa menjelajah puluhan situs dengan segmen, isi, dan jenis
bacaan yang mereka inginkan. Sayangnya, kemudahan akses ini pada beberapa
kasus, salah satunya adalah di tingkat pembaca remaja menimbulkan masalah.
Bukan hanya tentang waktu, yang lebih berbahaya adalah niai yang termuat di
dalamnya yang dapat dengan mudah mereka akses tanpa filter sama sekali.
Teman saya yang juga pembaca sastra siber mengungkapkan bahwa secara
normatif seperti tayangan televisi, umumnya penyedia novel online
telah memberi tanda khusus pada tiap karya yang disediakan sesuai segmen
pembaca yang diinginkan. Namun, sekali lagi karena bentuknya digital bagaimana
filter bisa diberlakukan? Lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia
dapat melakukan peran ini dengan mengatur jadwal tanyang televisi. Hal serupa
tentu sangat sulit dilakukan pada karya sastra siber. Bagaimana mengendalikan
jaringan dan keinginan membaca remaja di tangan mereka setiap saat? Sementara
kebebasan berkespresi di dunia digital begitu pesatnya. Hal yang patus kita
waspadai adalah nilai-nilai kebebasan seperti kekerasan, LGBT, seks bebas, dan
lainnya yang seharusnya belum dikonsumsi oleh segmen pembaca tertentu tidak
dapat kita hindari. Maka, benteng terakhir adalah orang tua dan sekolah yang
harus terus mengedukasi mereka agar menjadi pembaca cerdas dan kritis.
Perubahan memang sebuah keniscayaan. Sebagaimana seorang ahli mengugkapkan
hanya ada tiga pilihan kita berhadapan dengan perubahan. Apakah kita akan
menjadi pencipta, pengikut, atau penolak perubahan. Setidaknya meskipun belum
bisa menjadi kelompok pertama, semestinya kita bisa menjadi kelompok kedua yang
tetap kritis.
Tulisan ini telah dimuat di harian Gorontalo Pos edisi Rabu, 27 Januari
2022